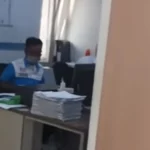Opini : Krisis Sunyi di Pasar Rakyat
Gelombang kenaikan harga kebutuhan pokok kembali menghantam masyarakat pada awal tahun ini. Beras, cabai, telur, minyak goreng, hingga gula mengalami lonjakan harga yang signifikan di berbagai daerah. Kondisi ini tidak hanya memicu keluhan di pasar tradisional, tetapi juga menimbulkan kegelisahan di ruang-ruang rumah tangga rakyat kecil yang setiap hari harus berjuang menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang kian terbatas.
Bagi sebagian masyarakat kelas menengah ke atas, kenaikan harga pangan mungkin hanya berarti penyesuaian gaya hidup. Namun bagi buruh harian, petani kecil, nelayan, dan pelaku usaha mikro, lonjakan harga adalah ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup. Ketika penghasilan tetap atau bahkan menurun, sementara kebutuhan pokok terus merangkak naik, pilihan yang tersisa hanyalah mengurangi kualitas konsumsi atau berutang demi bertahan.
Persoalan ini sejatinya bukan sekadar soal produksi. Pemerintah kerap menyampaikan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya jurang antara data di atas kertas dan realitas di pasar. Distribusi yang tidak merata, rantai pasok yang panjang, serta lemahnya pengawasan membuka ruang bagi praktik penimbunan dan spekulasi harga oleh segelintir pihak.
Ironi terbesar terletak pada posisi Indonesia sebagai negara agraris. Dengan tanah subur dan tenaga kerja di sektor pertanian yang besar, seharusnya ketahanan pangan menjadi kekuatan utama bangsa. Namun yang terjadi justru sebaliknya: petani sering merugi saat panen raya karena harga anjlok, sementara konsumen menjerit ketika pasokan berkurang dan harga melonjak. Situasi ini menandakan kegagalan tata kelola pangan dari hulu hingga hilir.
Di sisi lain, kebijakan impor kerap dijadikan jalan pintas untuk menstabilkan harga. Sayangnya, langkah ini sering tidak disertai perencanaan matang dan perlindungan terhadap petani lokal. Ketergantungan pada impor tanpa pembenahan struktural hanya akan melanggengkan persoalan yang sama di masa depan, sekaligus melemahkan kemandirian pangan nasional.
Narasi pemerintah yang mengimbau masyarakat untuk bersabar dan berhemat terdengar normatif dan cenderung mengabaikan realitas sosial. Kesabaran rakyat memiliki batas, terlebih ketika kebutuhan paling mendasar—makan—menjadi persoalan harian. Dalam konteks ini, negara dituntut tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga melalui kebijakan konkret yang berpihak pada kepentingan publik.
Penguatan peran Bulog, pemangkasan rantai distribusi, transparansi data stok pangan, serta penindakan tegas terhadap mafia pangan harus menjadi agenda serius, bukan sekadar wacana. Selain itu, kebijakan pangan perlu diletakkan dalam kerangka keadilan sosial, bukan semata logika pasar yang kerap mengorbankan kelompok rentan.
Kenaikan harga pangan sejatinya adalah cermin dari relasi negara dan rakyatnya. Ketika negara gagal menjamin akses terhadap kebutuhan dasar, kepercayaan publik akan perlahan terkikis. Stabilitas sosial dan ekonomi tidak mungkin terwujud tanpa kepastian bahwa setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan paling mendasar dengan layak.
 ">
">Pada akhirnya, isu harga pangan bukan sekadar soal naik-turun angka di pasar, melainkan soal martabat manusia. Negara diuji bukan dari seberapa sering pejabat berbicara, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu melindungi rakyat dari ketidakpastian hidup. Jika persoalan ini terus dibiarkan berulang, maka yang terancam bukan hanya daya beli, melainkan juga kepercayaan rakyat terhadap negara.